Hari Jadi Kota Probolinggo 663 (bagian 6) : Menegaskan Budaya Pandalungan Probolinggo
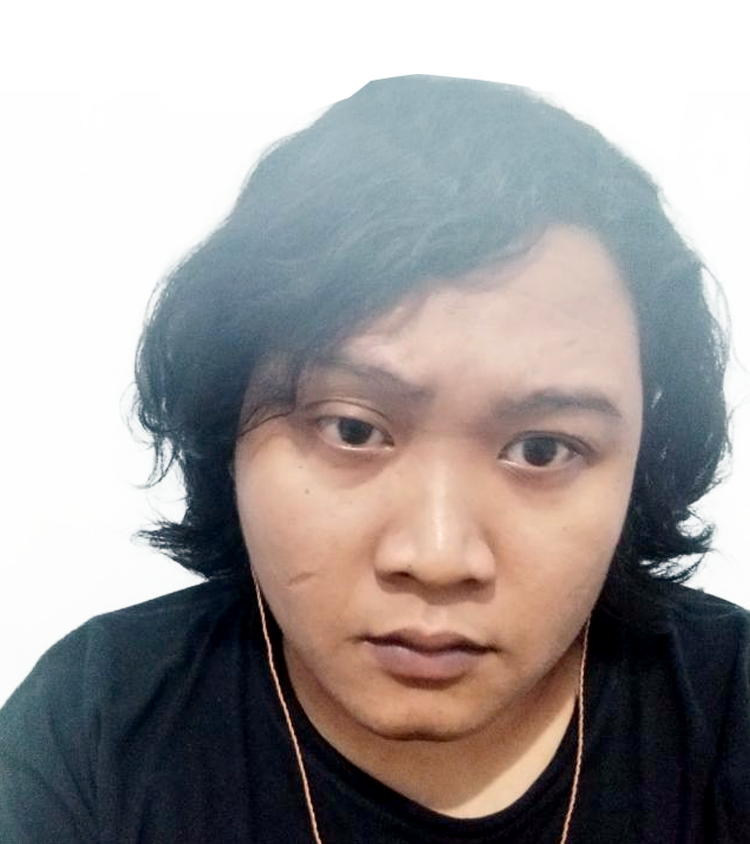
Iqbal Al Fardi
Sabtu, 03 Sep 2022 09:56 WIB

Dr. M. Ilham Zoebazary, M.Si | Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember
PROBOLINGGO merupakan salah satu daerah di wilayah tapal kuda Jawa Timur yang masyarakatnya teridentifikasi berbudaya pandalungan/pendalungan atau campuran. Interaksi terus menerus masyarakat berbeda latar belakang kultur di Probolinggo melahirkan pola budaya baru, hybrid, hasil pencampuran.
Di Kota Probolinggo, upaya identifikasi karakter budaya pandalungan Probolinggo telah dilakukan sejak awal 2000-an melalui beberapa kali forum seminar dan workshop. Namun, sejalan dengan akulturasinya yang masih terus in-progress, belum terlalu banyak pendaran budaya pandalungan Probolinggo bisa teridentifikasi selain bahasa dialek Probolinggoan yang juga masih minim.
Apa itu pandalungan? Apakah budaya pandalungan Probolinggo berarti hanya campuran Jawa dan Madura? Agar budaya pandalungan Probolinggo semakin tegas karakternya, apakah perlu langkah mendesain?
Sebagai salah satu bahan refleksi Hari Jadi Kota Probolinggo ke-663, jurnalis tadatodays.com Iqbal Al Fardi mewawancarai khusus dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember Dr. M. Ilham Zoebazary, M.Si, mengenai budaya pandalungan.
Di wilayah tapal kuda Jawa Timur ini daerah dengan budaya pandalungan ditemukan di mana saja?
Secara pembagian kewilayahan, Jawa Timur ini kan ada 10 wilayah kebudayaan. Salah satunya ini pandalungan. Pandalungan ini terbentang di wilayah Tapal Kuda, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, sampai ke Banyuwangi.
Kalau di Probolinggo kan ada sub etnis Tengger dan di Banyuwangi itu Osing. Selain itu, adalah orang-orang pandalungan ini. Tapi kan masalah identias kultural itu kembali ke masing-masing. Kalau orang tersebut tidak mau disebut sebagai orang pandalungan ya tidak masalah juga.
Tapi, untuk kepentingan studi sosiologi, misalnya, politik, kebudayaan, kita kan perlu identifikasi. Identifikasi semacam itulah yang kita perlukan. Secara global dan umum kita menyebut orang yang mendiami wilayah Tapal Kuda ini sebagai orang pandalungan, termasuk Probolinggo.
Apakah daerah yang sama berkultur pandalungan selalu sama identik, atau tetap memiliki perbedaan tegas?
Ya, meskipun kita menyebut sebagai orang pandalungan, tidak sama semuanya. Sama dengan orang Madura. Orang Madura itu yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, kemudian Sumenep itu berbeda-beda. Misalnya dari bahasa. Orang Sumenep itu menyebut katok itu saleber, makin ke sini ada sleber, sampai sini leber. Itu artinya tidak ada yang bisa dianggap sama. Meskipun mereka adalah orang Madura.
Apa lagi orang pandalungan. Pandalungan itu kan mix, ya, hybrid. Ada yang Jawa bercampur dengan Madura. Ada Jawa bercampur dengan Osing. Jawa bercampur dengan Arab. Ada yang Jawa dengan Jawa. Tapi karena menempati pandalungan, kita identifikasi sebagai pandalungan, berbeda-beda. Berbeda sekali.
Misalnya, nih, kalau yang Probolinggo itu sangat terpengaruh dengan kebudayaan Arek. Kebudayaan Arek itu, Malang, Surabaya. Nah, kebudayaan Arek tidak merembet sampai ke sini (Jember). Di Lumajang, iya. Sebagian terpengaruh kebudayaan Arek, Malang. Karena riwayat panjang, maka Osing juga berpengaruh.
Di Jember juga begitu. Madura sangat kuat pengaruhnya, satu bagian tertentu. Di bagian sebelah timur ini, Osing berpengaruh. Mandar di daerah selatan. Jadi itu, wilayah pandalungan berbeda-beda karena lingkungannya juga berbeda-beda, bermacam-macam.
Ambil contoh, kultur pandalungan di Probolinggo apakah sama dengan pandalungan di Jember?
Mengapa mereka disebut sebagai pandalungan, itu tentu ada benang merah yang menjadikan mereka sama. Kita identifikasi sebagai sama. Sebagian orang menganggap bahwa pandalungan itu adalah masyarakat campuran, hybrid antara Jawa - Madura.
Sebagian yang lain mengatakan “oh bukan. Bukan hanya itu. Jawa dengan Osing juga pandalungan. Jawa dengan Arab juga pandalungan.” Bahkan ada yang beranggapan, pandalungan itu kalau orang-orang setempat, misalnya orang Madura atau orang Jawa atau Osing yang kawin dengan orang Eropa, misalnya Portugis, Belanda, Inggris, itu adalah orang pandalungan. Tapi, secara keseluruhan itu ada persamaannya. Benang merahnya adalah campuran.
Pada daerah yang disebut berkultur pandalungan, apakah ada yang pencampurannya sudah merata di berbagai aspek?
Itu sporadis, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini orang pandalungan. Kecuali memang itu desa tradisional. Misalnya ada yang melakukan penelitian, di Probolinggo itu ada beberapa desa yang masyarakatnya berbahasa campuran Jawa - Madura secara seimbang 50 persen Jawa dan 50 persen Madura. Di tempat lain ada kandungan Maduranya lebih besar. Di tempat lain kandungan Jawanya lebih besar. Kecuali itu tadi, daerah-daerah yang memang secara tradisional turun-temurun sebagai orang setempat.
Lalu, pada umumnya daerah pandalungan, terjadi hibridisasi pada aspek apa yang terbanyak muncul paling menonjol?
Karena ini masalah kebudayaan, jadi hibridasi itu ada pada produk-produk kebudayaan. Membedakan kebudayaan dan yang bukan, itu gampang sekali. Misalnya yang bisa kelola itu kebudayaan. Kalau sungai atau laut itu kan alam, bukan kebudayaan. Tapi, sektor-sektor sekitar itu bisa kita atur, misalnya pertanian. Yang di dekat laut menjadi nelayan itu yang bisa kita atur. Itu adalah produk-produk kebudayaan. Ini yang membedakan orang per orang atau etnis, kelompok, berada di mana mereka. Kalau mereka berada di tempat yang lingkungan tertentu maka mereka akan menyesuaikan dengan lingkungannya itu. Di tempat lain juga begitu.
Ini akan menghasilkan varian-varian kebudayaan pandalungan. Sama dengan daerah-daerah lain, varian-varian kebudayaan semacam itu juga terjadi. Orang-orang di suatu tempat itu berkesenian. Kesenian itu jangan hanya dianggap sebagai tari-tarian, jaranan, reog. Itu salah satunya. Tapi ada produk-produk kebudayaan, kesenian, yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga sulit untuk kita identifikasi, misalnya pakaian. Seperti saat ini, kita sedang berkesenian sebenarnya. Seni berpakaian, menata rambut itu seni penataan rambut, dan yang lain-lain. Kuliner, macam-macam. Hal itu bervariasi dari satu tempat ke tempat lain karena memang pengaruh-pengaruh. Begitu.
Sebenarnya, apa urgensi atau nilai strategis “labelling” pandalungan bagi daerah?
Menurut saya, identitas kultural itu sangat diperlukan. Tapi, jangan salah, ya! Identitas kultural itu cair sifatnya. Artinya berlapis-lapis. Saya, suatu ketika cukup menyebut saya orang Indonesia ketika saya berada di Eropa, misalnya. Kalau saya menyebut saya orang pandalungan, saya orang Jawa, bingung mereka. Saya cukup menyebut saya orang Indonesia.
Di Jakarta ketika bertemu teman-teman di sana, saya boleh ketika saya berdiskusi masalah kebudayaan saya menyebut saya orang Jawa. Karena saya memang dilahirkan di lingkungan kebudayaan Jawa, orang tua saya Jawa. Tapi untuk kepentingan yang spesifik di Jawa Timur, ketika berdiskusi tentang pembagian wilayah, saya bisa menyebut bahwa saya orang pandalungan. Suatu ketika saya juga bisa menyebut saya orang Islam karena saya beragama Islam.
Jadi, identitas kultural itu bisa bervariasi. Ini penting karena sebagai ancer-ancer kita mau ke masa depan. Arah masa depan itu analoginya misalnya begini, kalau kita mau ke Surabaya, kamu ditanya “kamu mau ke Surabaya, sekarang ada di mana?” Jika jawabannya “Di mana ya ini?” tidak bisa memberi petunjuk, cari sendiri (jalannya). Tapi kalau jawabannya begini “Saya ada di FIB Unej”, maka jawabannya ialah “Oh, kalau begitu keluar ke sana, ke arah sana”.

Nah itu, mudah sekali ketika kita bisa menentukan kita berada di sini. Saya adalah orang pandalungan. Saya mengemban dan mendukung kebudayaan pandalungan. Maka, pengembangan kebudayaan saya begini dan begini. Misalnya semacam itu.
Berdasar penelitian dan kajian yang sudah pernah dilakukan Pak Ilham, bagaimana potret kultur pandalungan di Probolinggo? Apa ciri kultur pandalungan Probolinggo yang paling menonjol?
Probolingo ini tidak terlalu berbeda jauh dengan tempat-tempat lain, misalnya Lumajang dan Jember. Secara umum, ya. Tapi secara spesifik ada perbedaan-perbedaan yang spesifik itulah yang mestinya menjadi perhatian masyarakat atau pemerintah setempat untuk mengembangkan diri. Misalnya, bebeda dengan Jember.
Probolinggo itu adalah kota yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Kalau Jember sejarahnya cetek ya. Relatif pendek. Era Belanda perkebunan, tidak punya sampai tataran kerajaan. Tidak ada. Nah, Probolinggo punya itu. Seperti juga Lumajang. Punya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Probolinggo itu sudah ada jauh sebelum orang berpikir tentang nasionalisme. Belum berpikir tentang modernisme yang kita pahami sekarang. Itu di sana sudah ada kebudayaan yang berkembang.
Itu bisa digali dan dikembangkan menjadi Probolinggo modern yang tentu saja hasilnya akan berbeda dengan Jember atau Lumajang. Karena modal kultural yang dipunyai itu berbeda. Misalnya dalam hal kesenian. Kesenian di Probolinggo itu, selain kesenian secara umum dimiliki oleh orang Jawa, misalnya wayang kulit, ludruk, jaranan. Tapi ada yang spesifik, misalnya punya glipang, jaran bodak yang di tempat lain itu sulit ditemukan. Jaran bodak itu saya hanya menemukan di Probolinggo.
Di sana (Kota Probolinggo) juga ada lengger yang berbeda dengan lengger di Jember atau di Jawa Tengah, misalnya. Itu juga bisa dikembangkan. Tapi kan selama ini belum mendapat perhatian yang maksimal sehingga ini menjadi kekuatan yang bisa ditonjolkan. Belum lagi potensi yang tidak bersifat kultural, misalnya alam.
Probolinggo itu memiliki kekayaan lokal yang di tempat lain tidak ada dan orang Probolinggo sendiri yang tahu, yang harus mengembangkan itu, tugas pemerintah daerah. Tapi kita kan tidak bisa berharap terlalu banyak pada mereka. Yang bisa kita harapkan adalah orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Bergerak mengembangkan Probolinggo bersama pemerintah daerah.
Agar bahasa (dialek) pandalungan Probolinggo bisa semakin cepat berkembang, apa yang bisa dilakukan?
Menurut saya, bahasa pandalungan belum ada. Yang ada itu bahasa Jawa. Kalau di Jember itu dialek Jemberan. Probolinggo bisa kita sebut sebagai gaya Probolinggoan. Atau apapun, terserah kita mau namakan apa. Saya tidak terlalu optimis jika itu bisa berkembang secara optimal. Akan berkembang secara alamiah.
Mengapa tidak akan berkembang secara optimal? Karena pemerintah daerah Jawa Timur, misalnya, hanya mempunyai, di perda Jatim, yang dianggap sebagai bahasa daerah itu bahasa Jawa dan Madura. Sehingga orang Banyuwangi yang punya Osing tidak bisa mengembangkan secara optimal berdasarkan undang-undang karena tidak didukung oleh perundang-undangan.
Apalagi daerah lain seperti Probolinggo yang tidak punya latar belakang khusus mengenai kebahasaan. Jadi yang bisa kita kembangkan di sana ialah mengambangkan bahasa Jawa dan Madura yang diakui secara hukum. Masyarakat kalau mau berkembang dengan sendirinya, dialek mereka, kita tunggu saja bagaimana nanti. Secara natural.
Warga Probolinggo sampai kini masih kesulitan merumuskan busana pandalungannya Probolinggo. Apa yang ideal dilakukan? Mengikuti saja proses akulturasi secara alamiah sampai lahir sendiri karakter busana pandalungan Probolinggo, atau melakukan percepatan dengan langkah-langkah penciptaan yang cenderung top down?
Ada daerah tertentu yang secara kreatif masyarakatnya menciptakan sendiri. Ada yang memang top down. Mana yang lebih efektif? Ya, tergantung. Saya memberi contoh Jakarta. Jakarta itu dulu sebelum tahun 70-an, tidak ada orang yang menyebut dirinya “saya orang Betawi”.
Di Banyuwangi juga begitu. Menurut penelitian Bernard Arps tidak ada orang Banyuwangi yang menyebut dirinya itu “saya orang Osing”. Yang ada itu “saya orang Jawa Banyuwangi” atau “saya orang Jawa Osing”. Tapi sekarang, karena top down dan dibina sedemikian rupa, maka orang Osing menganggap dirinya berbeda dengan Jawa.
Sama dengan di Jakarta. Tahun 70-an di bawah Gubernur Ali Sadikin, mereka mengonstruksi dirinya itu: kita perlu kebudayaan daerah, kita perlu identitas lokal. Lalu mereka menggali. Ketemulah Betawi, berdasarkan pertimbangan tertentu. Sebelumnya, orang-orang menyebut dirinya “saya orang Melayu”. Kuningan ya Melayu Kuningan, tergantung daerah. Setelah 70-an mereka menyebut “saya orang Betawi”.
Bahasanya bagaimana? Ya, mereka mencari, mengonstruksi bahasa dialek mereka itu menyebut sebagai bahasa dialek Betawi. Perlu busana, dong. Ya, mereka menciptakan. Sampai ada busana None, Abang Jakarte. Itu diciptakan semuanya. Sampai, “wah ini perlu kuliner khas ini”. Lalu, mereka menggali Ketoprak, Kerak Telor.
Itu semuanya adalah konstruksi. Kebudayaan itu tidak ada yang tidak “by design”. Semuanya by design. Kalau tidak didesain, itu sebenarnya didesain oleh masyarakat. Tetapi, berjalan secara evolutif yang sangat panjang.
Kalau Probolinggo menunggu punya bahasa, busana dan kuliner sendiri, itu menunggu waktu yang sangat lama dan belum tentu tercapai. Tapi jika by design, top down misalnya, melalui lomba-lomba, kegiatan sosialisasi yang intensif, seminar-seminar, dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat. Itu bukan hal yang tabu. Boleh digunakan.
Jika ingin cepat, ya, top down. Dan meski dengan cara top down, masih belum tentu bisa diterima oleh masyarakat, loh. Misalnya, saya ambil contoh di Jember itu Tari Lahbako. Pemerintah daerah pada waktu itu menganggap kita perlu punya tari daerah. Maka dihadirkanlah Pak Bagong Kusudihardja dari Jogja untuk menciptakan tari dan dibantu oleh seniman tari dan musik Jember. Jadilah Tari Lahbako. Tetapi masyarakat masih tidak serta-merta menerima. Itu sudah berapa puluh tahun dan masyakarat sebagian besar enggan menerima Tari Lahbako sebagai tari tradisional Jember.
Jadi, dalam hal pengembangan dan penguatan budaya pandalungan, perlukah dilakukan semacam rekayasa sosial agar terjadi percepatan, atau dibiarkan saja terjadi akulturasi secara alamiah hingga lahir hibridisasi di berbagai aspek?
Idealnya, kita menunggu lama. Masyarakat itu melakukan kreativitasnya masing-masing. Nanti berkembang hingga kemudian ketemu. Ketika dulu transportasi dan komunikasi sulit, mereka terkotak sehingga mereka berkembang. Sekarang ini pengaruh-pengaruh. Yang ini belum jadi, sudah dipengaruhi dan seterusnya. Ya, tidak jadi-jadi.
Maka, saya kira yang lebih efektif adalah jika ingin punya design yang pasti adalah ciptakan lalu tawarkan ke masyarakat. Apakah setuju? Jika tidak setuju apa yang perlu dibenahi, dikreasi dan dikembangkan lagi. Itu, perlu dialog semacam itu. Tapi harus dilakukan. Kalau tidak, ya sulit. Dan harus berkesinambungan.
Nah, sayangnya di pemerintah daerah kita ini, tidak hanya di Pobolinggo ya, di manapun, kesinambungan berkelanjutan itu jarang terjadi. Kalau bupati atau walikotanya ganti, biasanya cenderung punya kebijakan yang baru dan menganggap semata-mata itu politis. Padahal, kebudayaan tidak bisa seperti itu. Kebudayaan memang perlu didukung oleh langkah-langkah politis. Tapi butuh waktu yang panjang, dari satu walikota/bupati ke walikota/bupati berikutnya yang ada kesinambungan itu. Kalau tidak, ya tidak akan jadi apa-apa. (iaf/why)
.png)
.png)


Share to
 (lp).jpg)