Ironi Suro Wiro Aji Busono: Saat Identitas Kota Lahir dari Rahim Nirempati
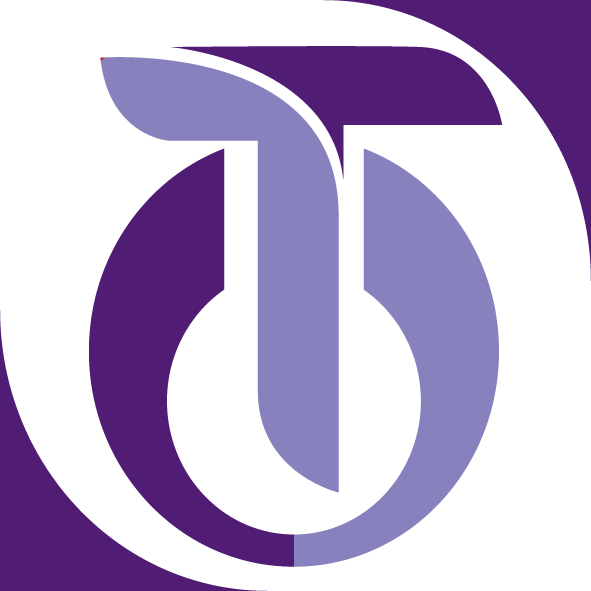
Tadatodays
Monday, 09 Feb 2026 13:33 WIB

PERAYAAN Hari Jadi Kota Pasuruan ke-340 digelar dengan penuh kemeriahan. Jalan-jalan kota dihiasi ornamen budaya, panggung pertunjukan berdiri megah, dan masyarakat larut dalam suasana sukacita kolektif.
Di tengah arus kebanggaan itu, sebuah simbol baru diperkenalkan kepada publik: busana khas “Suro Wiro Aji Busono”. Busana ini digadang-gadang sebagai representasi identitas baru kota—sebuah penanda visual yang merangkum sejarah, nilai filosofis, dan semangat masyarakat Pasuruan.
Sebagai bagian dari tim formatur yang merumuskan konsep, estetika, dan filosofi busana tersebut, muncul rasa haru sekaligus bangga ketika karya intelektual itu dikenakan oleh para pemimpin dan warga kota. Ia bukan sekadar kostum seremonial, melainkan hasil dari proses panjang: riset sejarah lokal, dialog budaya, diskusi akademik, serta pergulatan kreatif yang tidak ringan.
Namun, di balik gemerlap perayaan dan sorotan publik, tersimpan pengalaman personal yang justru menorehkan luka batin—sebuah ironi yang menempatkan kebanggaan berdampingan dengan kekecewaan.
.png)
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan saat mengenakan busana suro wiro aji busono di momen hari jadi Kota Pasuruan.
Busana sebagai Narasi Identitas Kolektif
BUSANA daerah tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia adalah narasi visual yang memuat pesan tentang masa lalu dan harapan masa depan. Dalam konteks “Suro Wiro Aji Busono”, proses kreatif melibatkan upaya merangkai simbol-simbol lokal—mulai dari sejarah kepemimpinan Pasuruan, nilai keberanian dan kebijaksanaan, hingga estetika yang mampu menyatukan keragaman identitas masyarakat.
Proses perumusan bukan sekadar teknis desain. Ia menuntut pemahaman mendalam tentang sejarah kota, hubungan kekuasaan, serta dinamika sosial budaya masyarakat. Para formatur bekerja dengan semangat gotong royong, berharap hasilnya menjadi warisan budaya yang membanggakan.
Namun, ketika karya tersebut akhirnya diresmikan, muncul pertanyaan fundamental: sejauh mana negara—dalam hal ini pemerintah kota—menghargai proses intelektual di balik produk budaya yang mereka adopsi?
Ketimpangan Apresiasi Materiil
POIN pertama yang menjadi sorotan adalah rendahnya nilai apresiasi materiil yang diberikan kepada tim formatur. Dalam banyak praktik kebijakan budaya, penghargaan finansial bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan pengakuan atas nilai kerja kreatif. Ketika nominal yang diberikan terasa tidak sebanding dengan beban kerja dan nilai simbolik karya yang dihasilkan, muncul kesan bahwa kontribusi intelektual dianggap remeh.
Fenomena ini bukan hanya persoalan individu, tetapi mencerminkan paradigma birokrasi yang sering memandang kerja kreatif sebagai aktivitas “tambahan” yang bisa dinegosiasikan secara minimal. Padahal, produk budaya yang dihasilkan kemudian menjadi aset publik—dipakai secara resmi, dipromosikan secara luas, dan berpotensi menjadi identitas jangka panjang kota.
Hilangnya Apresiasi Simbolis dan Etika Pengakuan

SELAIN materiil, aspek simbolis juga menjadi persoalan penting. Dalam budaya Jawa, konsep nguwongke—memanusiakan manusia—merupakan nilai luhur yang menekankan penghargaan terhadap kontribusi individu. Ketika tim formatur tidak dilibatkan dalam seremoni resmi atau bahkan tidak disebutkan sebagai pencipta karya, muncul rasa keterasingan dari produk yang mereka lahirkan sendiri.
Pengakuan simbolis seperti penyebutan nama, pemberian piagam, atau undangan resmi bukan sekadar formalitas. Ia adalah bentuk legitimasi sosial yang menegaskan bahwa karya budaya lahir dari kolaborasi, bukan semata-mata dari institusi. Ketika pengakuan itu hilang, proses kreatif terasa seperti kerja sunyi yang diambil alih tanpa penghormatan.
Nirempati sebagai Gejala Birokrasi
ISTILAH “nirempati” muncul sebagai kritik terhadap sikap birokrasi yang dianggap kehilangan sensitivitas sosial. Kemewahan acara peresmian kontras dengan minimnya perhatian terhadap para kreator. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak emosional antara lembaga pemerintah dan masyarakat kreatif yang justru menjadi sumber inovasi budaya.
Dalam konteks pembangunan kota, empati bukan sekadar nilai moral, tetapi strategi keberlanjutan. Kota yang mampu merawat hubungan sehat dengan komunitas kreatif akan memiliki ekosistem budaya yang kuat. Sebaliknya, jika kolaborasi dilandasi oleh praktik yang tidak adil atau kurang menghargai, kepercayaan publik dapat terkikis.
Dampak Jangka Panjang terhadap Ekosistem Kreatif
KASUS ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana pemerintah daerah memperlakukan pekerja kreatif. Apabila pengalaman serupa terus berulang, dampaknya bisa meluas: menurunnya minat kolaborasi, berkurangnya partisipasi komunitas budaya, hingga lahirnya jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil. Kota mungkin tetap memiliki simbol budaya, tetapi kehilangan jiwa kolektif yang seharusnya menyertainya.
Pembangunan identitas kota seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil visual atau seremoni publik, melainkan juga pada proses yang adil dan manusiawi. Penghargaan yang layak—baik secara materiil maupun simbolis—menjadi investasi sosial yang menjaga keberlanjutan kreativitas lokal.
Refleksi dan Harapan ke Depan
TULISAN ini bukan sekadar keluhan personal, melainkan refleksi kritis atas praktik kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat kreatif. Harapannya, pengalaman ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan standar kerja yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan. Misalnya, melalui kontrak kerja yang jelas, mekanisme penghargaan yang proporsional, serta pengakuan publik yang layak terhadap para kreator.
“Suro Wiro Aji Busono” seharusnya menjadi simbol kebanggaan bersama—bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para perumusnya. Identitas kota akan memiliki jiwa jika lahir dari proses yang menghargai manusia di baliknya. Kota yang besar bukan hanya diukur dari kemegahan acara atau simbol fisiknya, tetapi dari kemampuannya menjaga martabat warganya.
Semoga kritik terbuka ini menjadi cermin reflektif, bukan sekadar suara yang hilang di tengah riuh perayaan. Karena pada akhirnya, karya budaya yang lahir dari empati akan hidup lebih lama dalam ingatan kolektif masyarakat dibandingkan simbol yang tercipta tanpa penghargaan terhadap para penciptanya.
* Penulis adalah Seniman dan Anggota Tim Formatur


Share to
 (lp).jpg)